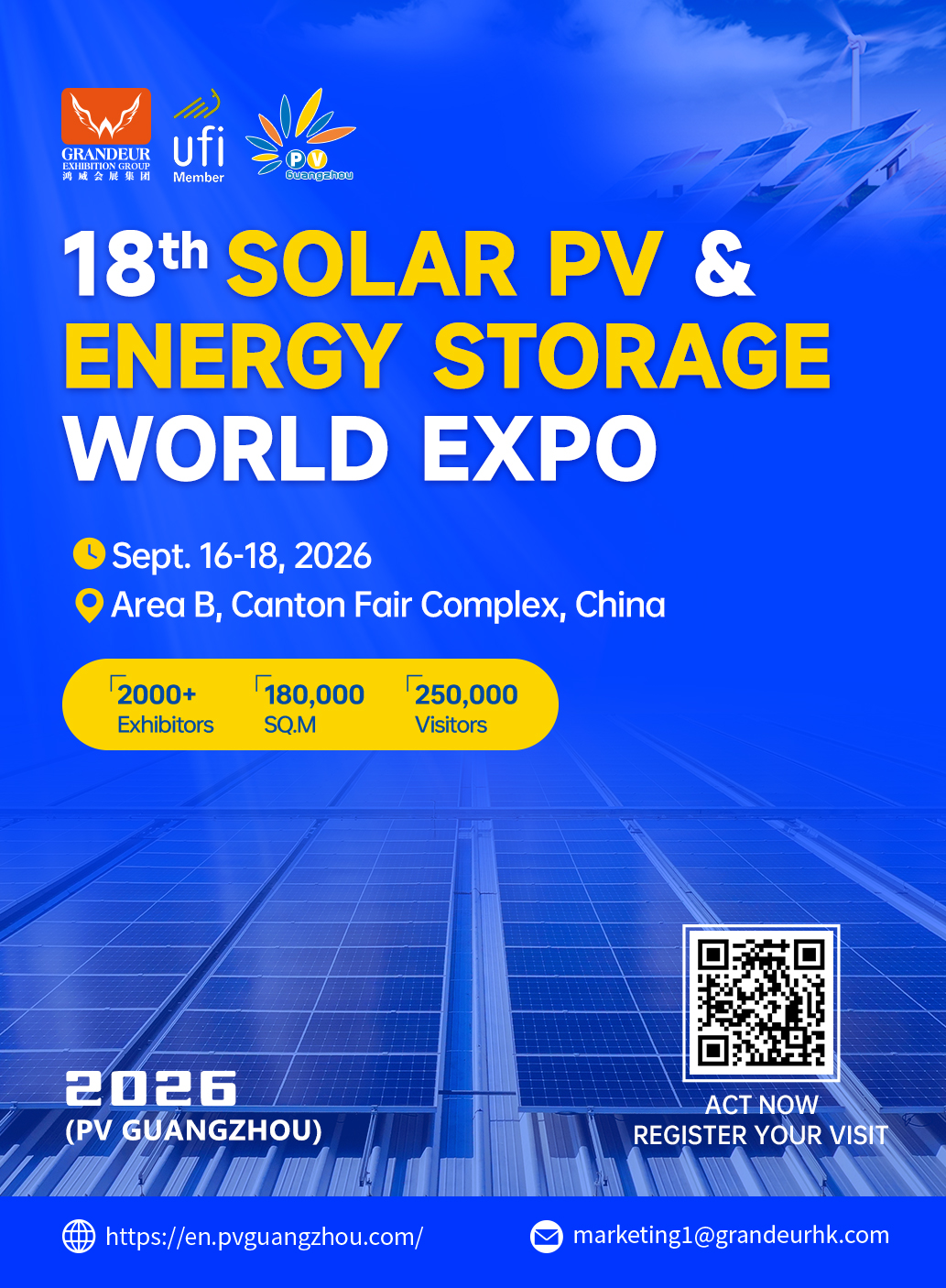Ecobiz.asia — Integrasi tata ruang ekologis dan ekonomi berbasis One Map Policy dengan pendekatan lanskap berkelanjutan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi konflik pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang kian kompleks di Indonesia.
Demikian terungkap dari policy brief berjudul “Konflik Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Alam antara Pembangunan Ekonomi dan Konservasi,” yang dirancang Kelompok 3 Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV Tahun 2025 Lembaga Administrasi Nasional (LAN), dikutip Jumat (24/10/2025).
Laporan tersebut menyoroti meningkatnya ketegangan antara upaya hilirisasi dan industrialisasi dengan agenda konservasi lingkungan serta perlindungan masyarakat adat. Ketidaksinkronan regulasi antar kementerian, lemahnya penegakan hukum, dan dominasi pembangunan ekstraktif disebut menjadi faktor utama yang memperburuk konflik lahan.
Data Kementerian Kehutanan dan Global Forest Watch (2024) mencatat Indonesia kehilangan sekitar 216 ribu hektare hutan alam dalam setahun. Lebih dari 1.200 komunitas adat juga terdampak langsung oleh tumpang tindih lahan dan konflik agraria.
Kondisi ini tidak hanya menyebabkan deforestasi dan degradasi ekosistem, tetapi juga meningkatkan emisi karbon serta menimbulkan ketimpangan sosial yang berujung pada tingginya biaya pemulihan lingkungan.
“Pembangunan ekonomi tidak harus bertentangan dengan konservasi lingkungan. Dengan tata ruang yang terintegrasi dan pendekatan lanskap berkelanjutan, hilirisasi dapat berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem,” demikian Policy Brief tersebut.
Kelompok 3 Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV mendorong perlunya reformasi tata kelola lahan yang adaptif, transparan, dan inklusif.
Salah satunya melalui penerapan sistem zonasi dinamis berbasis data geospasial yang mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan ekonomi.
Moratorium izin baru di kawasan bernilai konservasi tinggi juga dipandang penting untuk mencegah degradasi lebih lanjut, sementara pelibatan masyarakat adat dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) diharapkan menjadi fondasi baru dalam perencanaan ruang dan pengambilan keputusan.
Dari sisi ekonomi, penguatan insentif fiskal bagi industri hijau seperti sertifikasi ramah lingkungan dan kredit karbon dinilai dapat mempercepat transisi menuju sistem produksi yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi satelit dan big data untuk pemantauan kawasan hutan, serta pembentukan lembaga mediasi independen dalam penyelesaian konflik lahan, juga direkomendasikan untuk memperkuat sistem pengawasan dan keadilan tata kelola sumber daya alam.
Rekomendasi ini dinilai sejalan dengan target FOLU Net Sink 2030 dan dapat memperkuat posisi Indonesia menghadapi EU Deforestation Regulation 2025 yang menuntut transparansi rantai pasok komoditas berbasis lahan.
“Kolaborasi multipihak antara pemerintah, korporasi, akademisi, dan masyarakat adat akan menjadi kunci menuju pembangunan berkelanjutan yang adil, inklusif, dan berdaya saing global,” demikian kesimpulan policy brief tersebut. ***