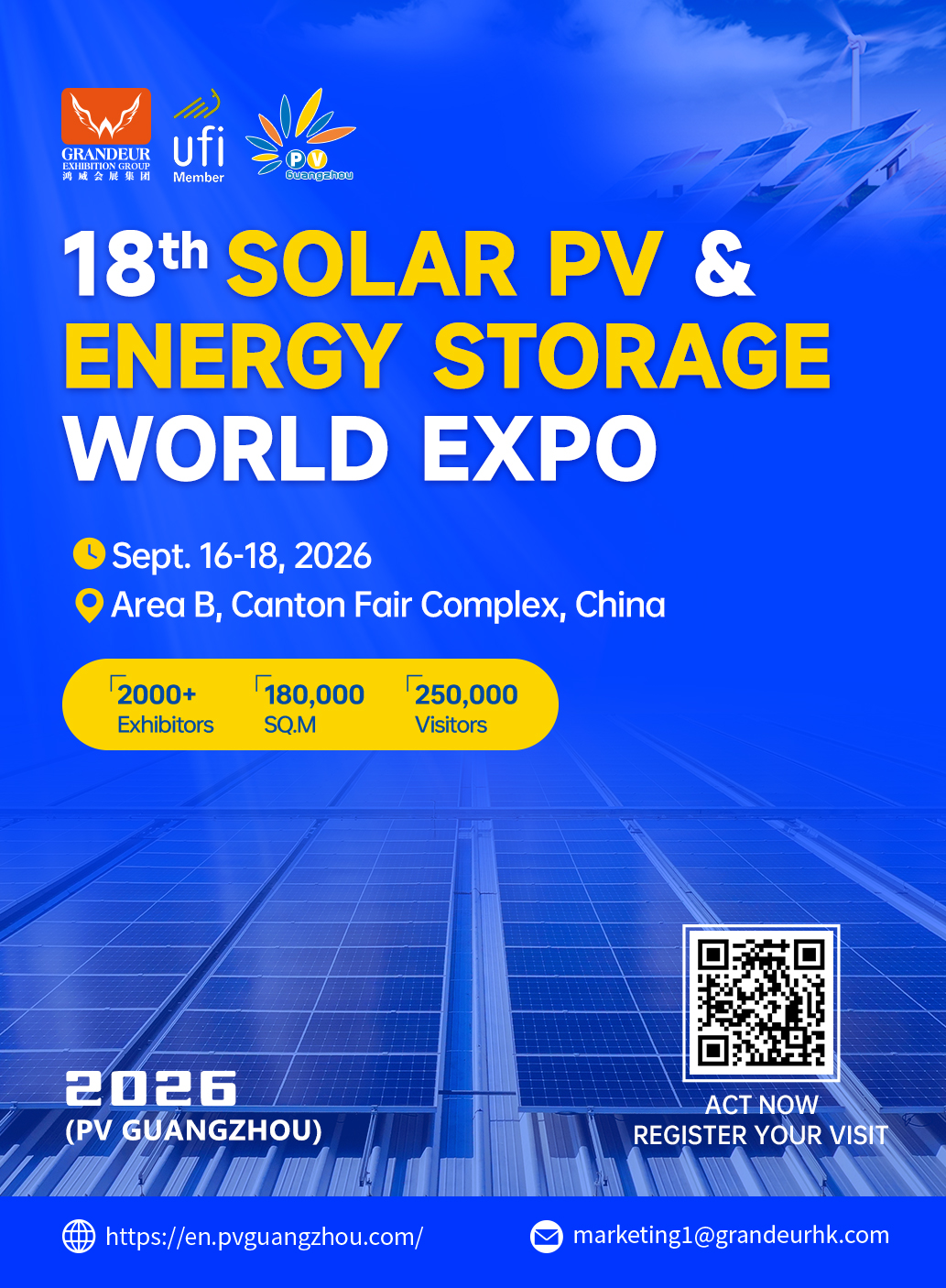Oleh: Dr. Eka W. Soegiri [Praktisi Penyuluhan, Ketua Umum Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO) tahun 2018 – 2023 – 2025, Ketua Harian Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional tahun 2016 – 2019]
Ecobiz.asia – Wacana penarikan penyuluh kehutanan dari daerah ke pusat saat ini tengah mencuat. Gagasan ini mencerminkan keinginan untuk memperkuat kendali dan efektivitas penyuluhan, mengikuti langkah serupa yang ditempuh oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Namun, jika tidak ditelaah dengan cermat, langkah tersebut berisiko memutus mata rantai komunikasi, koordinasi, dan pendampingan di tingkat tapak, tempat penyuluh bekerja dan berinteraksi langsung dengan masyarakat hutan.
Perlu dipahami, kedua instansi tersebut tidak memangku kawasan, beda dengan Kemenhut.

Penyuluhan: Simpul Implementasi Kebijakan Kehutanan
Penyuluhan kehutanan bukan sekadar kegiatan edukatif di lapangan. Ia adalah simpul koordinasi implementasi kebijakan kehutanan di tingkat tapak yang menghubungkan visi dan kebijakan di pusat dengan realitas di lapangan.
Tugas utama penyuluh adalah melakukan perubahan knowledge, skill, dan attitude masyarakat pengelola hutan agar mampu beradaptasi dengan kebijakan dan praktik pengelolaan hutan lestari.
Sasaran penyuluhan terbagi tiga: sasaran utama (pelaku di tingkat tapak seperti Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial), sasaran penunjang (akademisi, praktisi, dunia usaha, dan politisi), serta sasaran penentu (pembuat kebijakan di seluruh tingkatan pemerintahan).
Fungsi penyuluhan adalah memastikan seluruh strata birokrasi dan pelaku lapangan memiliki visi, interpretasi, dan persepsi yang seragam terhadap arah kebijakan kehutanan nasional. Tanpa keseragaman itu, implementasi di lapangan akan bias, tumpang-tindih, dan tidak efektif.
Secara hukum, sistem penyuluhan diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), yang menempatkan kelembagaan penyuluhan secara berjenjang dari pusat hingga kecamatan melalui Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) dan Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh).
Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah lanskap kelembagaan tersebut secara drastis. Kewenangan penyuluhan menjadi tidak sejajar antar sektor: penyuluhan pertanian tetap menyebar di semua tingkatan pemerintahan, sementara penyuluhan kehutanan dan perikanan sebagian besar ditarik ke pusat dan provinsi.
Akibatnya, fungsi penyuluhan di tingkat kabupaten dan kota menjadi kabur, bahkan terfragmentasi di bawah berbagai dinas teknis. Banyak penyuluh kehutanan yang semula memiliki tugas pendampingan kini terjebak dalam pekerjaan administratif atau non-teknis di luar mandat penyuluhan.
Belakangan Kementerian Pertanian berencana menarik seluruh penyuluh pertanian menjadi pegawai pusat mulai 2026 untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, menyusul apa yang sudah terjadi pada Kementerian Perikanan. Wacana untuk mengimplementasikan kebijakan serupa pada Kehutanan pun mengemuka.
Perlu diingat, dengan jumlah saat ini sekitar 10.050 penyuluh kehutanan di 38 provinsi, di mana 2.600 di antaranya berstatus ASN, kontribusi penyuluh kehutanan tidak bisa dipandang kecil. Mereka menjadi pendamping langsung Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mencatat nilai ekonomi sekitar Rp4 triliun per tahun. Ini bukti nyata bahwa penyuluhan bukan beban birokrasi, melainkan investasi sosial-ekologis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi hutan.
Menakar Ulang Gagasan Sentralisasi
Penarikan penyuluh ke pusat memang menjanjikan keseragaman komando dan kebijakan, seperti pada era sentralisasi penyuluhan pertanian di tahun 1970–1980-an. Namun konteksnya berbeda.
Penyuluh pertanian bekerja dengan komoditas dan produktivitas yang relatif seragam, dengan target mencapai swasembada beras, sementara penyuluh kehutanan bekerja di wilayah yang kompleks: hutan lindung, produksi, konservasi, hingga perhutanan sosial, dengan karakter sosial-ekologis yang sangat beragam.
Jika penyuluh ditarik ke pusat tanpa kesiapan kelembagaan dan sumber daya, fungsi pendampingan langsung akan melemah. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kemenhut saat ini hanya memiliki tujuh balai untuk seluruh Indonesia jelas tidak sebanding dengan luas kawasan hutan dan sebaran masyarakatnya.
Penempatan penyuluh di UPT teknis lain pun tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, kecuali dilakukan restrukturisasi kelembagaan yang menempatkan fungsi penyuluhan sebagai core function, bukan sekadar “titipan”. Bila tidak, penyuluh hanya akan menjadi pelengkap administrasi, bukan agen perubahan sosial.
Transformasi: Dari Birokrasi ke Gerakan Pengetahuan
Yang mendesak hari ini bukanlah memindahkan penyuluh secara administratif, melainkan mentransformasikan fungsi penyuluhan menjadi gerakan pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat.
Penyuluh harus dibekali kemampuan analisis sosial, komunikasi lintas aktor, serta akses terhadap teknologi dan data lapangan. Dalam era perubahan iklim, peran penyuluh tidak lagi sebatas penyampai pesan, tetapi menjadi arsitek sosial-ekologis yang membantu masyarakat mengelola sumber daya hutan secara adaptif dan berkelanjutan.
Transformasi ini menuntut investasi serius dalam penguatan kapasitas, sistem karier, dan penghargaan terhadap kinerja penyuluh. Undang-Undang SP3K seharusnya menjadi dasar untuk membangun kembali “rumah besar penyuluhan” yang sempat hilang setelah perubahan kelembagaan pasca-UU 23/2014.
Penutup: Menata Ulang, Bukan Menarik ke Pusat
Wacana menarik penyuluh kehutanan ke pusat memang perlu dikaji, tetapi bukan solusi tunggal. Penyuluhan adalah jembatan antara kebijakan dan masyarakat. Menariknya ke pusat justru berisiko memutus rantai komunikasi yang telah lama dibangun di tingkat tapak.
Yang dibutuhkan bukan sentralisasi, tetapi sinkronisasi kelembagaan dan revitalisasi peran: memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan, menegaskan posisi penyuluhan sebagai simpul implementasi kebijakan, dan memastikan setiap penyuluh bekerja dalam sistem yang menghargai keilmuan dan integritas.
Transformasi penyuluhan kehutanan harus dimaknai sebagai proses penataan ulang yang berorientasi pada penguatan fungsi dan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar perubahan struktur birokrasi. ***