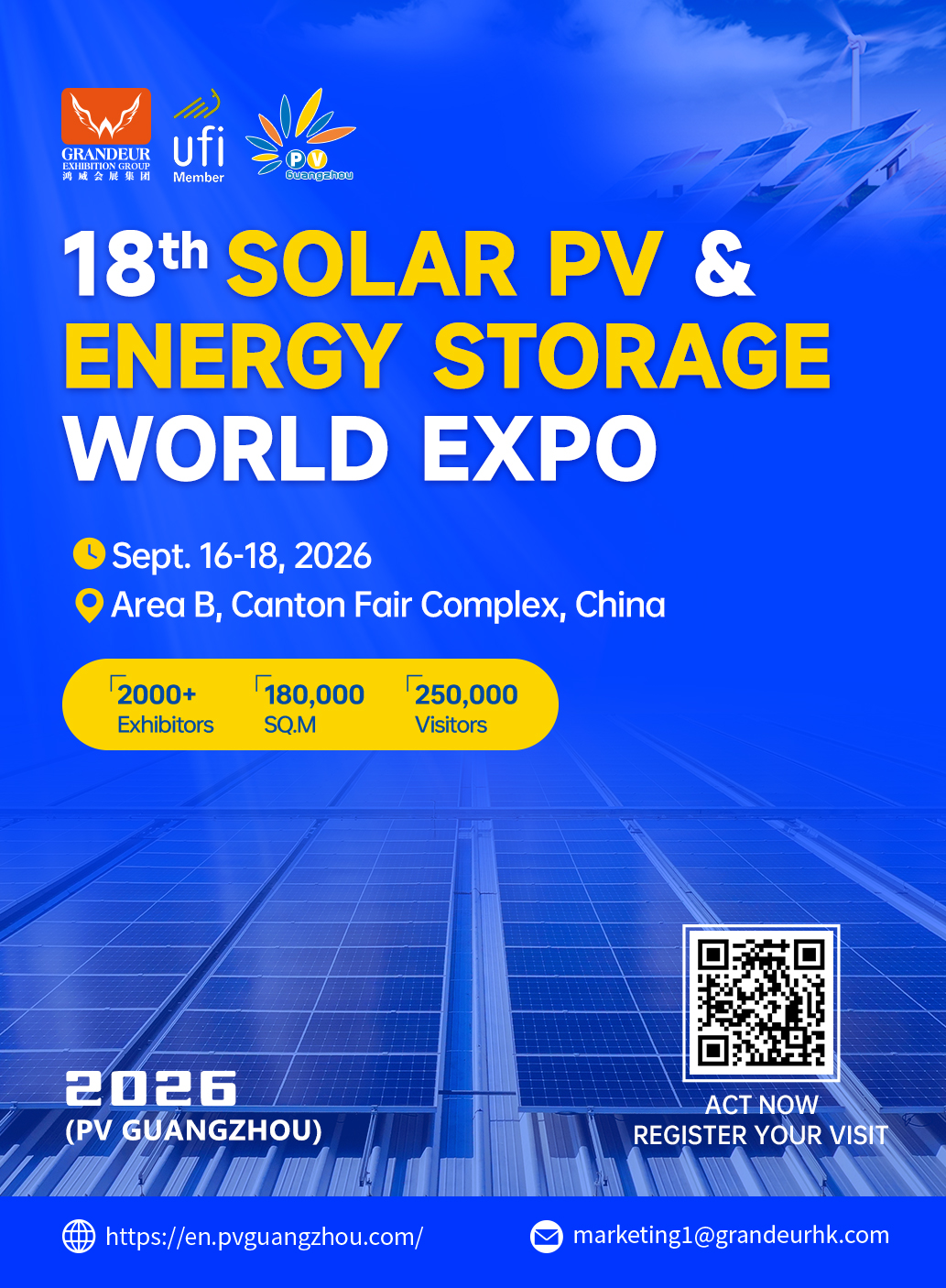Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
Ecobiz.asia – Tulisan Kuntoro Boga, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, di Kompas.com (21/8/2025) berjudul “Menjaga Hutan, Menggerakkan Ekonomi” menghadirkan optimisme besar terhadap program perhutanan sosial melalui konsep agroforestri. Menurutnya, dari luas 8,3 juta hektare perhutanan sosial, komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, karet, pala, dan kelapa bisa disinergikan dalam pola agroforestri sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga hutan. Contoh yang sering diangkat adalah Desa Sarongge di Cianjur, Jawa Barat. Di sana, 35 petani mengelola 21,2 hektare kopi dalam pola agroforestri dan sukses menembus pasar ekspor ke Jerman. Tidak berhenti pada kopi, pemerintah bahkan memproyeksikan jutaan hektare perhutanan sosial menjadi lumbung pangan strategis dengan padi gogo, jagung, hingga umbi-umbian.
Sekilas, semua itu terdengar menjanjikan. Tetapi pertanyaannya, apakah contoh Sarongge yang luasnya hanya puluhan hektare bisa dijadikan representasi jutaan hektare perhutanan sosial yang tersebar di berbagai pulau di luar Jawa? Apakah konsep agroforestri yang dikembangkan di sana benar-benar sesuai dengan kaidah ilmu kehutanan? Bagaimana dengan kesiapan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) di lapangan, dan apakah produk perkebunan yang ditanam di dalam kawasan hutan tidak akan berbenturan dengan regulasi perdagangan global, khususnya European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang melarang produk dari lahan berisiko deforestasi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat optimisme tadi terasa seperti fatamorgana.
Agroforestri sejatinya adalah praktik pengelolaan hutan yang mengombinasikan tanaman kayu dengan tanaman pertanian. Dalam literatur kehutanan, konsep ini kerap dipandang sebagai solusi menjaga fungsi ekologis sekaligus memberi ruang penghidupan. Di Indonesia, regulasi yang ada juga mendukungnya. PP No. 26/2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, misalnya, mengatur bahwa reboisasi bisa dilakukan melalui agroforestri, baik di lahan kritis, semak belukar, kebun, maupun lahan pertanian masyarakat. Aturan lain, seperti PP No. 23/2021 dan Permen LHK No. 7/2021, membuka peluang kawasan hutan lindung dan hutan produksi digunakan untuk food estate apabila kondisinya terbuka atau terdegradasi. Bahkan, Permen LHK No. P.105/2018 merinci komposisi agroforestri yang ideal: setiap hektare harus ditanami minimal 400 batang tanaman pokok atau 75 persen dari total luas, sementara sisanya bisa berupa tanaman sela, pagar, atau sekat bakar seperti lamtoro, gamal, kopi, dan kaliandra.
Di atas kertas, aturan-aturan itu tampak jelas. Namun praktik di lapangan jauh lebih kompleks. Pada hutan produksi, tumpangsari dengan tanaman semusim memang diperbolehkan hingga tanaman pokok berusia delapan tahun. Tetapi begitu pohon mencapai diameter di atas 35 sentimeter atau sekitar umur 13 tahun, tumpangsari harus dihentikan agar tegakan hutan bisa tumbuh optimal. Di hutan lindung, syaratnya lebih ketat lagi: jarak tanam rapat dua kali tiga meter atau tiga kali tiga meter sehingga setiap hektare menampung sekitar 1.500 batang pohon. Selain itu, harus diterapkan teknik konservasi tanah seperti rorak atau terjunan air untuk mencegah erosi. Semua ini menegaskan bahwa agroforestri bukan sekadar menanam kopi di sela pohon, melainkan sistem pengelolaan yang kompleks dan disiplin.
Ketika pemerintah menyampaikan bahwa perhutanan sosial sudah mencapai 8,3 juta hektare dari target 12,7 juta hektare, angka itu memang terlihat impresif. Namun ukuran luas semata tidak otomatis menggambarkan kualitas. Dari sisi ekonomi dan lingkungan, capaian program masih jauh dari harapan. Perhutanan sosial sejatinya berdiri di atas tiga pilar: kemandirian masyarakat, peran penyuluh atau pendamping, dan fasilitasi pemerintah. Tanpa kemandirian kelompok dalam mengelola lahan, tanpa keterampilan penyuluh dalam membina, dan tanpa dukungan pemerintah dalam perizinan, permodalan, serta pemasaran, program akan mandek.
Indikator konkret ada pada perkembangan kelompok usaha perhutanan sosial. Dari 15.766 KUPS yang terbentuk, hanya 120 masuk kategori platinum dan 1.350 berstatus gold. Itu berarti hanya 9,32 persen yang dianggap mandiri, jauh dari standar ideal yang seharusnya mencapai 75 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar KUPS masih rapuh dan bergantung pada bantuan.
Distribusi perhutanan sosial pun timpang. Lebih dari 90 persen arealnya berada di luar Jawa, dengan sebaran terbesar di Papua Selatan 840 ribu hektare, Kalimantan Utara 547 ribu hektare, Kalimantan Tengah 507 ribu hektare, dan Sulawesi Selatan 452 ribu hektare. Sementara di Pulau Jawa, luas perhutanan sosial tidak sampai 400 ribu hektare. Kondisi tanah juga menjadi faktor penghambat. Di luar Jawa, lahan umumnya berupa tanah podsolik merah kuning yang miskin hara dan banyak mengandung logam berat, atau berupa lahan gambut yang rentan rusak. Tanah-tanah seperti ini tidak cocok untuk komoditas kopi, kakao, atau padi gogo tanpa intervensi mahal seperti pengapuran dan pemupukan intensif. Biaya yang tinggi jelas tidak sebanding dengan hasil, sehingga secara usaha tani tidak ekonomis.
Di Jawa, kendati tanah vulkanis relatif subur, masalahnya lain. Praktik agroforestri kerap menyimpang dari aturan. Seharusnya 70 persen areal ditanami tanaman hutan dan 30 persen sisanya untuk tanaman non-hutan, tetapi di banyak tempat komposisi ini terbalik. Di Hutan Lindung Mandalawangi, Garut, misalnya, tanaman kopi jauh lebih dominan dibanding tegakan hutan. Alih-alih memperkuat konservasi, pola seperti ini justru memperbesar risiko sedimentasi dan longsor, sesuatu yang berlawanan dengan prinsip agroforestri.
Masalah lain datang dari luar negeri. Negara-negara Uni Eropa kini memperketat aturan perdagangan dengan memberlakukan European Union Deforestation Regulation. Regulasi ini efektif 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar, melarang masuknya produk yang berasal dari lahan berisiko deforestasi. Komoditas yang terkena dampak bukan hanya kopi, kakao, dan karet, tetapi juga sawit, kedelai, sapi, serta kayu dan seluruh turunannya. Bagi produk agroforestri dari kawasan hutan—baik itu hutan produksi, lindung, maupun konservasi—risikonya jelas: mereka bisa ditolak pasar.
Contoh kopi Sarongge yang selama ini dianggap sukses bisa sewaktu-waktu terhambat jika tidak lolos sertifikasi EUDR. Dan perlu diingat, regulasi semacam ini kemungkinan besar tidak hanya berhenti di Uni Eropa. Amerika Serikat dan negara-negara maju lain bisa mengikuti langkah serupa. Jika tata kelola agroforestri di Indonesia tidak segera dibenahi, optimisme tentang masa depan ekonomi perhutanan sosial hanya akan menjadi fatamorgana: indah dari kejauhan, tetapi kosong ketika didekati. ***