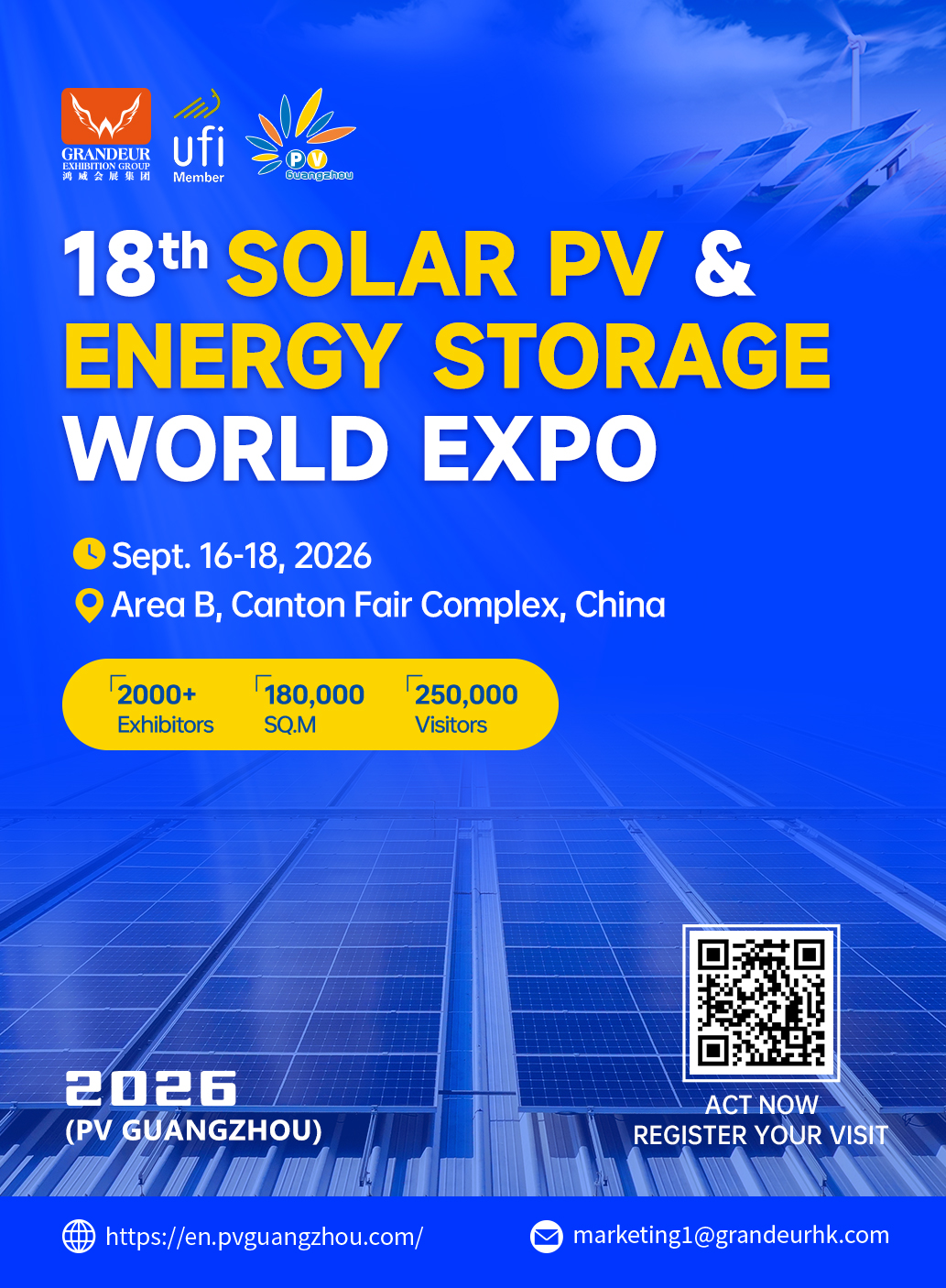Ecobiz.asia – Kebijakan tarif baru Amerika Serikat telah menambah babak penting dalam hubungan dagang dengan Indonesia. Angka 19% yang ditetapkan bukan sekadar statistik, melainkan sinyal kuat bahwa dinamika perdagangan global kini semakin sarat dengan kalkulasi politik, proteksi industri, sekaligus negosiasi strategis. Bagi Indonesia, terutama sektor kayu dan furnitur yang selama ini bergantung pada pasar Amerika, tarif ini menghadirkan tantangan nyata: bagaimana menjaga daya saing di tengah biaya tambahan yang signifikan. Namun di balik itu, terbuka pula ruang refleksi, apakah beban tarif ini hanya akan menjadi pukulan, atau justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat branding legalitas, memperluas pasar, dan menata ulang strategi ekspor kayu Indonesia di masa depan.
Membaca strategi dagang AS dan pilihan sulit yang dihadapi industri kayu Indonesia.
Untuk memahami dampak kebijakan ini secara lebih mendalam, langkah pertama adalah melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan tarif 19%, bagaimana cakupan penerapannya, dan sejauh mana aturan ini berbeda dari rezim tarif sebelumnya
Tarif 19% merupakan ketentuan baru dalam kerangka hubungan dagang resiprokal antara Amerika Serikat dan Indonesia yang mulai diberlakukan pada pertengahan 2025. Dalam perjanjian ini, Indonesia mengambil langkah besar dengan menghapus sekitar 99% tarif bea masuk bagi produk-produk asal Amerika, sebuah komitmen yang menunjukkan keterbukaan pasar. Sebagai gantinya, Amerika Serikat menerapkan tarif resiprokal sebesar 19% terhadap barang-barang asal Indonesia. Meskipun terdengar berat, terdapat ruang fleksibilitas: beberapa komoditas yang tidak diproduksi atau tidak tersedia secara alami di AS berpotensi mendapat penurunan tambahan, tergantung hasil negosiasi lanjutan di tingkat teknis dan diplomatik (The White House).
Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tarif 19% ini berdiri di atas tarif umum yang sudah ada dalam Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS, Column 1). Artinya, tarif ini bersifat tambahan ad valorem, bukan pengganti. Misalnya, jika suatu produk kayu Indonesia semula bebas bea (0%), maka dengan kebijakan ini ia akan dikenakan 19%. Namun bila suatu produk sebelumnya sudah memiliki tarif umum 8%, maka tarif efektif total menjadi 27%. Ketentuan ini ditegaskan dalam Executive Order 14257 dan modifikasi per 31 Juli 2025, yang secara resmi mencantumkan Indonesia dengan tarif 19%, Vietnam 20%, Thailand 19%, dan Malaysia 19%. Sebagai bentuk pengawasan, U.S. Customs and Border Protection (CBP) juga menetapkan penalti tambahan sebesar 40% apabila ada praktik pengelakan (transshipment) yang terbukti (The White House).
Kebijakan ini bukan sekadar rumor atau wacana. Implementasi dan pemberlakuannya telah dikonfirmasi langsung melalui pernyataan resmi Gedung Putih serta dilaporkan oleh media internasional seperti Reuters, yang menyoroti tenggat waktu implementasi dan dinamika negosiasi antara Washington dan mitra dagang Asia Tenggara. Dengan kata lain, bagi Indonesia, terutama sektor kayu dan furniture, tarif 19% kini menjadi realitas yang harus diantisipasi dengan serius.
Dengan pemahaman tentang mekanisme dan cakupan tarif 19% ini, pertanyaan berikutnya yang lebih krusial adalah: berapa besar beban biaya tambahan yang ditanggung produk kayu Indonesia, mulai dari furnitur premium hingga plywood untuk konstruksi, dan bagaimana hal itu berpengaruh pada daya saing di pasar Amerika Serikat.
Dampak nyata tarif resiprokal terhadap margin, daya saing, dan strategi ekspor kayu Indonesia.
Penerapan tarif baru sebesar 19% oleh Amerika Serikat bukan hanya soal regulasi dagang di atas kertas. Dampaknya terasa langsung di meja perhitungan eksportir kayu Indonesia: margin tergerus, harga jual naik, dan daya saing di pasar internasional dipertaruhkan. Bagi industri furnitur jati dan mahoni yang selama ini menempati segmen premium, beban tarif mungkin masih bisa dialihkan ke konsumen yang menghargai kualitas. Namun bagi plywood dan panel kayu yang bersaing di segmen massal, kenaikan biaya sekecil apa pun bisa menjadi penentu kalah atau menang dalam tender global. Inilah alasan mengapa tarif 19% perlu dilihat bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai ujian strategis bagi kelangsungan ekspor kayu Indonesia ke Negeri Paman Sam.
Furnitur Kayu: Tetap Dominan tapi Kian Terbebani
Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Januari–November 2024, ekspor furnitur dan kerajinan kayu Indonesia ke Amerika Serikat mencapai sekitar USD 2,22 miliar—menyumbang lebih dari separuh (53,6%) dari total ekspor furnitur Indonesia global. Angka ini jauh lebih besar dibanding estimasi 2023 (USD 1,3 miliar). Dengan skala sebesar itu, penerapan tarif tambahan 19% berpotensi membebani nilai ekspor hingga USD 421 juta hanya dari sektor furnitur.
Bagi furnitur premium berbahan jati, mahoni, dan rotan, pasar AS mungkin masih mampu menyerap kenaikan harga. Namun, risiko besar terletak pada segmen menengah yang lebih sensitif harga, di mana buyer bisa beralih ke produk Vietnam yang lebih efisien secara biaya.
Plywood dan Panel Kayu: Semakin Terjepit
Sepanjang 2024, ekspor plywood dan panel kayu Indonesia ke Amerika Serikat tercatat sebesar USD 431,5 juta. Dengan tambahan tarif 19%, beban tarif mencapai sekitar USD 82 juta. Bahkan untuk subpos dengan tarif umum 8%, total tarif efektif bisa melonjak ke 27%—setara tambahan USD 116 juta per tahun.
Kondisi ini membuat plywood Indonesia semakin sulit bersaing di segmen konstruksi massal, karena buyer Amerika sangat sensitif terhadap harga. Jika tidak ada strategi diferensiasi (misalnya plywood premium atau ramah lingkungan), risiko pergeseran permintaan ke Vietnam atau Tiongkok makin besar.
Produk Kayu Lain: Tekanan Kompetitif Tinggi
Produk kayu lain seperti moulding, veneer, dan komponen rumah tangga berbasis kayu jumlahnya relatif lebih kecil dibanding furnitur atau plywood. Namun tetap terkena tambahan tarif 19%. Karena sifatnya pelengkap dan mudah diganti dengan produk substitusi dari negara lain, segmen ini sangat rentan ditinggalkan buyer jika harga naik akibat tarif baru.
Dengan data 2024, jelas bahwa beban tarif terbesar akan ditanggung sektor furnitur kayu (USD 2,22 miliar nilai ekspor; potensi beban tarif ±USD 421 juta). Plywood tetap menjadi sektor paling rapuh karena pasar konstruksi lebih sensitif harga. Dengan ekspor USD 431,5 juta, tambahan tarif membuat daya saing plywood Indonesia kian melemah. Produk kayu lainnya tetap tertekan, meski skala nilai ekspornya lebih kecil.
Dengan data baru ini, bisa disimpulkan bahwa tarif 19% berpotensi menggerus hingga setengah miliar dolar AS nilai perdagangan kayu Indonesia di pasar Amerika setiap tahun, jika tidak ada strategi mitigasi melalui premiumisasi produk, diplomasi perdagangan, maupun diversifikasi pasar.
Tabel Dampak Tarif 19% per Produk Kayu Indonesia (Data 2024)
| Produk | Nilai Ekspor 2024 (USD juta) | Tarif Umum (HTSUS) | Tambahan Tarif Resiprokal | Total Efektif | Estimasi Beban Tarif 19% (USD juta) | Catatan Dampak |
| Furnitur & Kerajinan | 2220.0 | 0% | 19% | 19% | 422.0 | Segmen premium masih bisa menyerap, tapi beban total sangat besar (±USD 422 juta). |
| Plywood & Panel | 431.5 | 0–8% | 19% | 19–27% | 82.0 | Sangat rentan; buyer konstruksi sensitif harga, potensi kalah bersaing. |
| Produk Kayu Lain | 50.0 | 0–5% | 19% | 19–24% | 9.5 | Skala kecil, tapi mudah tergantikan buyer jika harga naik. |
Sumber: Digabungkan data resmi ekspor 2024 (Global Wood, Xinhua, UN/Trading Economics) dengan regulasi tarif (EO 14257, Reuters) serta estimasi tambahan untuk kategori minor.
Tarif 19% dalam Praktik: Apa Artinya per Produk Kayu?
Di pasar Amerika Serikat, perhitungan tarif didasarkan pada nilai pabean (CIF), yaitu harga barang ditambah ongkos kirim dan asuransi. Dengan kebijakan baru, tarif 19% ini ditambahkan di atas tarif umum yang tercantum pada (HTSUS). Dampaknya berbeda tergantung jenis produk kayu yang diekspor.
Furnitur Kayu (HS 9403.60)
Untuk furnitur kayu, tarif umum yang berlaku dalam HTSUS untuk banyak pos adalah 0% alias bebas bea. Dengan adanya tarif resiprokal 19%, beban total menjadi sekitar 19% dari nilai CIF. Hal ini juga ditegaskan dalam sejumlah dokumen klasifikasi resmi, misalnya untuk kode 9403.60.8093 yang bea umumnya 0%.
Sebagai ilustrasi sederhana: jika sebuah kursi kayu asal Indonesia diekspor dengan nilai CIF USD 550 per unit, maka tambahan tarif 19% berarti importir harus membayar USD 104,50 per unit di luar biaya lain seperti Merchandise Processing Fee (MPF) dan Harbor Maintenance Fee (HMF). Beban tambahan ini cukup signifikan, meski untuk segmen furnitur premium (jati, mahoni, rotan) pasar Amerika relatif masih bisa menyerapnya karena konsumen menghargai kualitas dan keunikan produk.
Plywood & Panel Kayu (HS 4412)
Untuk plywood dan panel, situasinya lebih rumit. Banyak subpos memang 0%, tetapi ada juga yang dikenai tarif umum 8%, seperti plywood berbahan bambu (HS 4412.10.0500). Dengan tambahan tarif 19%, maka total bea yang berlaku menjadi:
- Jika tarif umum 0% → total 19%, atau USD 190 per ton untuk CIF USD 1.000.
- Jika tarif umum 8% → total 27%, atau USD 270 per ton untuk CIF USD 1.000.
Bagi plywood, angka ini adalah pukulan besar. Pasar konstruksi di AS sangat sensitif terhadap harga; tambahan biaya puluhan hingga ratusan dolar per ton bisa langsung menggeser buyer ke pemasok lain seperti Vietnam atau Tiongkok.
Kondisi plywood makin kompleks sejak 16 Juni 2025, ketika Pemerintah AS menginisiasi penyelidikan anti-dumping (AD) dan countervailing duties (CVD) atas produk hardwood & decorative plywood dari Tiongkok, Indonesia, dan Vietnam. Jika investigasi ini berujung pada penetapan bea AD/CVD, maka pungutan tersebut akan menumpuk di atas tarif resiprokal 19%. Artinya, beban total bisa melampaui 30% bahkan 40%, membuat daya saing plywood Indonesia di pasar Amerika semakin rapuh.
Tarif 19% yang menekan margin, menguji kepatuhan, sekaligus membuka ruang lobi dagang
Penerapan tarif resiprokal 19% memberi tekanan langsung pada margin keuntungan eksportir kayu Indonesia. Importir dan retailer besar di Amerika Serikat cenderung tidak mau menanggung seluruh beban biaya ini, sehingga mereka berusaha menekan pemasok untuk berbagi kerugian. Tekanan ini semakin kuat pada produk yang harus bersaing langsung dengan negara tetangga seperti Vietnam (20%), Thailand (19%), dan Malaysia (19%). Artinya, Indonesia memang tidak sendirian menghadapi kebijakan ini, tetapi persaingan intra-ASEAN menjadi semakin ketat. Dalam situasi seperti ini, buyer memiliki keleluasaan untuk memilih pemasok mana yang paling efisien, bukan sekadar siapa yang paling murah.
Dampak tarif juga sangat berbeda antara produk bernila tambah tinggi dan produk komoditas massal. Furnitur kayu berbahan jati dan mahoni, yang dipasarkan sebagai produk premium, memiliki elastisitas harga lebih rendah. Dengan kata lain, konsumen Amerika masih bersedia membayar lebih mahal karena kualitas, desain, dan citra tropis yang ditawarkan. Sebaliknya, produk panel generik seperti plywood atau veneer lebih sulit mentransfer beban biaya ke konsumen akhir, karena pasar konstruksi sangat sensitif terhadap kenaikan harga sekecil apa pun.
Selain itu, ada risiko kepatuhan yang perlu diantisipasi. Pemerintah AS memberlakukan penalti hingga 40% tambahan tarif apabila terbukti ada praktik penghindaran aturan (transshipment) melalui negara ketiga. Hal ini menuntut eksportir Indonesia untuk menjaga transparansi asal-usul barang dan memastikan jalur logistik yang bersih, karena satu kesalahan bisa berdampak fatal pada reputasi sekaligus biaya.
Terakhir, terdapat faktor ketidakpastian waktu. Meskipun tarif 19% sudah diumumkan, detail mengenai implementasi penuh, termasuk pengecualian bagi komoditas yang tidak diproduksi di AS, masih dalam tahap negosiasi. Bagi Indonesia, ruang ketidakpastian ini bisa menjadi celah lobi strategis. Misalnya, produk berbasis rotan atau bambu, yang jelas tidak diproduksi secara komersial di Amerika, bisa didorong untuk masuk daftar pengecualian. Hasil akhir dari proses ini akan sangat menentukan seberapa berat dampak tarif terhadap masing-masing jenis produk kayu Indonesia.
Dengan kata lain, tarif 19% bukan hanya masalah hitungan bea, melainkan ujian daya saing: apakah Indonesia mampu menegaskan posisi furnitur premiumnya, memperketat kepatuhan logistik, sekaligus memanfaatkan ruang diplomasi untuk melindungi produk yang paling rentan.
Akhir Analisis, Awal Strategi Baru
Tarif resiprokal 19% yang diberlakukan Amerika Serikat membawa dampak berbeda bagi tiap segmen produk kayu Indonesia. Furnitur kayu relatif lebih aman karena nilai produknya tinggi dan citra premium jati, mahoni, serta rotan membuat konsumen Amerika masih bersedia membayar harga yang lebih mahal. Dengan strategi branding yang tepat, furnitur Indonesia masih dapat mempertahankan daya tariknya di pasar yang kompetitif.
Sebaliknya, plywood dan panel kayu berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Dengan tarif total yang bisa mencapai 27%, bahkan berpotensi lebih tinggi jika ditambah bea anti-dumping (AD) dan countervailing duties (CVD), produk ini menghadapi risiko serius kehilangan daya saing. Pasar konstruksi di Amerika sangat sensitif terhadap harga, sehingga kenaikan biaya sekecil apa pun dapat memicu buyer untuk beralih ke pemasok alternatif seperti Vietnam atau Tiongkok.
Untuk itu, strategi mitigasi menjadi kunci. Indonesia perlu fokus pada diversifikasi produk premiumyang mampu menjaga margin meski harga naik, termasuk memperkuat narasi keunggulan jati, mahoni, dan rotan. Di saat yang sama, pemerintah dan asosiasi industri harus aktif melakukan lobbying untuk pengecualian tarif bagi komoditas tertentu—misalnya rotan dan bambu—yang jelas tidak diproduksi di Amerika Serikat. Terakhir, industri perlu meningkatkan efisiensi melalui pengendalian biaya produksi dan logistik, agar daya saing tetap terjaga meskipun beban tarif tinggi tidak bisa sepenuhnya dihindari. Dengan kombinasi strategi tersebut, Indonesia bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga berpeluang memposisikan dirinya sebagai pemasok kayu tropis premium yang legal, berkelanjutan, dan tetap kompetitif di pasar Amerika Serikat. ***
Oleh: Diah Suradiredja (Pemerhati perdagangan berkelanjutan)