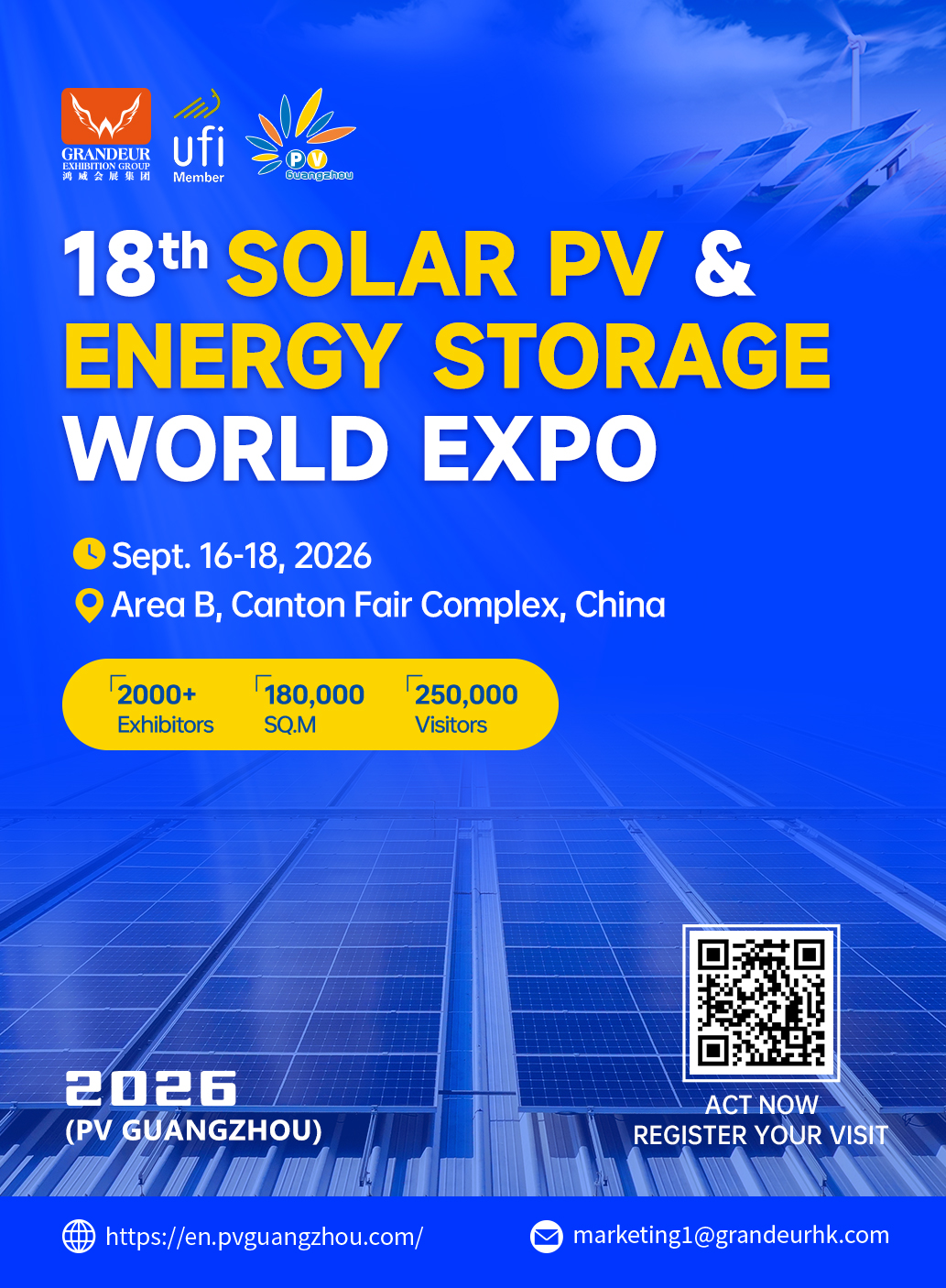Oleh: Diah Suradiredja (Pemerhati perdagangan komoditas berkelanjutan)
Ecobiz.asia – Di tengah gegap gempita wacana sawit berkelanjutan dan ekspor nikel hijau, ada satu komoditas lama yang nyaris terlupakan padahal memiliki potensi besar menjadi ikon ekonomi hijau Indonesia: karet alam.
Selama lebih dari seabad, karet menjadi bagian penting dari denyut ekonomi pedesaan Indonesia, menghubungkan petani di Jambi, Kalimantan, dan Sumatra Utara dengan industri ban di Eropa dan Jepang. Kini, komoditas ini berada di persimpangan: bertahan sebagai sektor tradisional yang tertinggal, atau bertransformasi menjadi bagian dari ekonomi hijau global.
Karet: Komoditas Strategis yang Terpinggirkan
Di antara komoditas unggulan seperti sawit, kopi, dan nikel, karet sering luput dari perhatian dalam percakapan ekonomi hijau nasional. Padahal, komoditas ini masih menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga petani.
Menurut BPS (2023), luas perkebunan karet Indonesia mencapai sekitar 3,15 juta hektare pada 2024, dengan Sumatra Selatan sebagai provinsi terluas (772 ribu hektare). Namun luas tersebut menurun drastis dari 3,78 juta hektare pada 2021. Artinya, hampir 600 ribu hektare kebun karet hilang hanya dalam dua tahun, sebagian karena alih fungsi lahan ke sawit dan tanaman pangan, sebagian karena kebun tua tak diremajakan.
Dari sisi produksi, Indonesia masih berada di posisi kedua dunia setelah Thailand, dengan produksi 2,65 juta ton pada 2023. Namun produktivitasnya tertinggal: hanya 0,8–1,1 ton per hektare per tahun, dibanding 1,7–2 ton di Thailand dan Malaysia. Keterbatasan bibit unggul, lemahnya manajemen kebun, serta minimnya investasi teknologi penyadapan menjadi penyebab utama.
Lebih dari 85% perkebunan dikelola oleh petani kecil dengan lahan di bawah dua hektare. Struktur yang terfragmentasi ini membuat posisi tawar petani lemah terhadap pengepul dan pabrik crumb rubber. Akibat rantai pasok panjang dan sulit dilacak, sebagian besar nilai tambah justru mengalir ke tengkulak dan pedagang besar.
Sebagian besar karet Indonesia (75–80%) diekspor dalam bentuk bahan mentah, dengan tujuan utama Jepang, AS, China, India, dan Korea Selatan. Ketergantungan ini membuat petani sangat rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Ketika harga jatuh, mereka kehilangan insentif untuk bertahan di sektor ini.
Kini tekanan datang dari regulasi global, seperti European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), yang mewajibkan pembuktian asal lahan bebas deforestasi untuk semua produk karet yang masuk ke pasar Eropa. Tanpa sistem ketelusuran nasional yang kredibel, jutaan petani Indonesia berisiko kehilangan akses pasar.
Namun di balik tantangan ini, tersembunyi peluang strategis. Dengan model agroforestri, pembiayaan hijau, dan sistem ketelusuran nasional, karet dapat kembali menjadi simbol ketahanan ekonomi rakyat sekaligus pilar transisi hijau.
Tekanan Global dan Peluang Transformasi Hijau
Dunia tengah bergerak menuju rantai pasok bebas deforestasi, dan Uni Eropa menjadi pionir melalui kebijakan EUDR yang berlaku pada Desember 2024. Setiap produk, termasuk karet, harus memiliki bukti geolokasi lahan dan jaminan bahwa produksinya tidak menyebabkan deforestasi setelah 31 Desember 2020.
Meski tujuannya baik, kebijakan ini dapat menjadi bumerang bagi petani kecil yang tidak memiliki dokumen legal lahan atau data spasial terverifikasi. “EUDR bisa menjadi pisau bermata dua. Jika Indonesia tidak memiliki sistem nasional yang kredibel, jutaan petani bisa kehilangan pasar meski mereka tidak pernah menebang hutan,” ujar seorang analis di Kemenko Perekonomian.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah membangun National Dashboard Komoditas Strategis (NDKS), platform lintas sektor yang memetakan lahan, petani, dan rantai pasok komoditas utama seperti karet, sawit, kopi, dan kakao. Melalui sistem ini, risiko deforestasi dapat diverifikasi tanpa membuka data mentah yang sensitif. NDKS juga menjadi instrumen diplomasi, agar pengawasan rantai pasok dilakukan berbasis risiko nasional, bukan tekanan sepihak.
Karet sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia
Karet bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan pilar ekonomi hijau yang menghubungkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan lingkungan. Tajuk pohon karet menahan erosi, akarnya menjaga kelembapan tanah, dan kebun karet berfungsi sebagai penyerap karbon di luar kawasan hutan formal.
Melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3, aktivitas seperti peremajaan kebun, sistem tanam agroforestri, dan perlindungan area bernilai konservasi tinggi (HCS–HCV) diakui sebagai kegiatan hijau. Ini membuka akses pembiayaan melalui green bonds, sustainability-linked loans, dan skema Payment for Ecosystem Services (PES) bagi petani dan koperasi.
Peluang besar terletak pada Perhutanan Sosial, yang mencakup lebih dari 8,5 juta hektare di seluruh Indonesia. Banyak di antaranya cocok untuk dikembangkan menjadi agroforestri karet rakyat, sistem tanam campuran antara karet, buah, dan tanaman kehutanan lokal.
Di Jambi dan Kalimantan Barat, kelompok perhutanan sosial yang menanam Hevea agroforest berhasil menjaga tutupan pohon di atas 70%, mengurangi erosi, dan tetap memperoleh pendapatan reguler dari lateks dan hasil hutan bukan kayu. Jika didukung sistem ketelusuran nasional dan insentif hijau, agroforestri karet dapat menjadi model ekonomi hijau inklusif yang menggabungkan pengentasan kemiskinan, perlindungan ekosistem, dan kepatuhan terhadap regulasi global seperti EUDR dan CSDDD.
Kelembagaan, Gender, dan Jejak Sosial Keberlanjutan
Transformasi sektor karet memerlukan penguatan kelembagaan petani. Dari dua juta rumah tangga petani karet, sebagian besar belum tergabung dalam koperasi. Kelemahan ini membatasi akses pembiayaan dan pelatihan. Pemerintah bersama mitra internasional kini mendorong pembentukan koperasi karet berkelanjutan, yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi sekaligus pusat data dan verifikasi petani.
Selain itu, dimensi sosial, terutama peran perempuan harus diakui. Banyak perempuan terlibat dalam penyadapan dan pengolahan, tetapi kontribusinya jarang tercatat. Standar keberlanjutan kini mulai memasukkan indikator kesetaraan gender, K3, dan jaminan sosial ke dalam praktik baik (Good Agricultural Practices).
Diplomasi Hijau dan Posisi Indonesia di Dunia
Indonesia berupaya mengubah perannya dari sekadar pengikut menjadi pembentuk norma keberlanjutan global. Melalui Joint Task Force (JTF) EUDR dengan Uni Eropa dan Malaysia, Indonesia mendorong mutual recognition antar sistem nasional seperti ISPO, SVLK, dan NDKS. Di tingkat ASEAN, Indonesia memimpin pembentukan ASEAN Sustainable Rubber Framework (ASRF) untuk menetapkan prinsip bersama bagi produsen regional.
Strategi diplomasi ini menunjukkan bahwa karet bukan hanya urusan agrikultur, tetapi bagian dari politik ekonomi hijau. Dengan sistem nasional yang kredibel, Indonesia bukan hanya mempertahankan akses pasar, tetapi juga memperjuangkan agar standar global menghormati konteks sosial-ekonomi negara produsen.
Karet, Masa Depan, dan Keadilan Iklim
Jika dikelola dengan visi jangka panjang, karet dapat menjadi model pembangunan hijau inklusif: meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga hutan tetap berdiri, dan memperkuat diplomasi ekonomi berkelanjutan. Dalam kerangka Pembangunan Rendah Karbon (LCDI), Bappenas memperkirakan sektor AFOLU termasuk karet, dapat menyumbang 1,2 gigaton pengurangan emisi CO₂e dan menciptakan lebih dari 4 juta pekerjaan hijau pada 2045.
Dari Getah ke Ketahanan
Karet mungkin lahir dari masa lalu, tetapi masa depannya masih terbuka lebar. Dalam upaya menuju ekonomi hijau, karet tidak lagi sekadar bahan baku ekspor, melainkan simbol ketahanan ekologi dan ekonomi rakyat. Melalui pendekatan agroforestri karet di areal Perhutanan Sosial, Indonesia memiliki peluang unik untuk menghubungkan dua agenda besar yang selama ini berjalan terpisah: pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kebun karet yang dikelola dengan sistem agroforestri di kawasan perhutanan sosial terbukti mampu menjaga tutupan pohon, menahan erosi, serta menyerap karbon dalam jumlah signifikan, sembari menyediakan pendapatan reguler dari lateks, buah, dan hasil hutan bukan kayu. Model ini menjadikan masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga penjaga lanskap dan pelaku utama ekonomi hijau.
Menghidupkan kembali karet berarti menghidupkan kembali harapan desa. Di bawah naungan pohon-pohon karet yang lestari, pembangunan berkelanjutan Indonesia menemukan akarnya: ekonomi rakyat yang tangguh, lingkungan yang terjaga, dan keadilan iklim yang berkeadilan sosial. ***