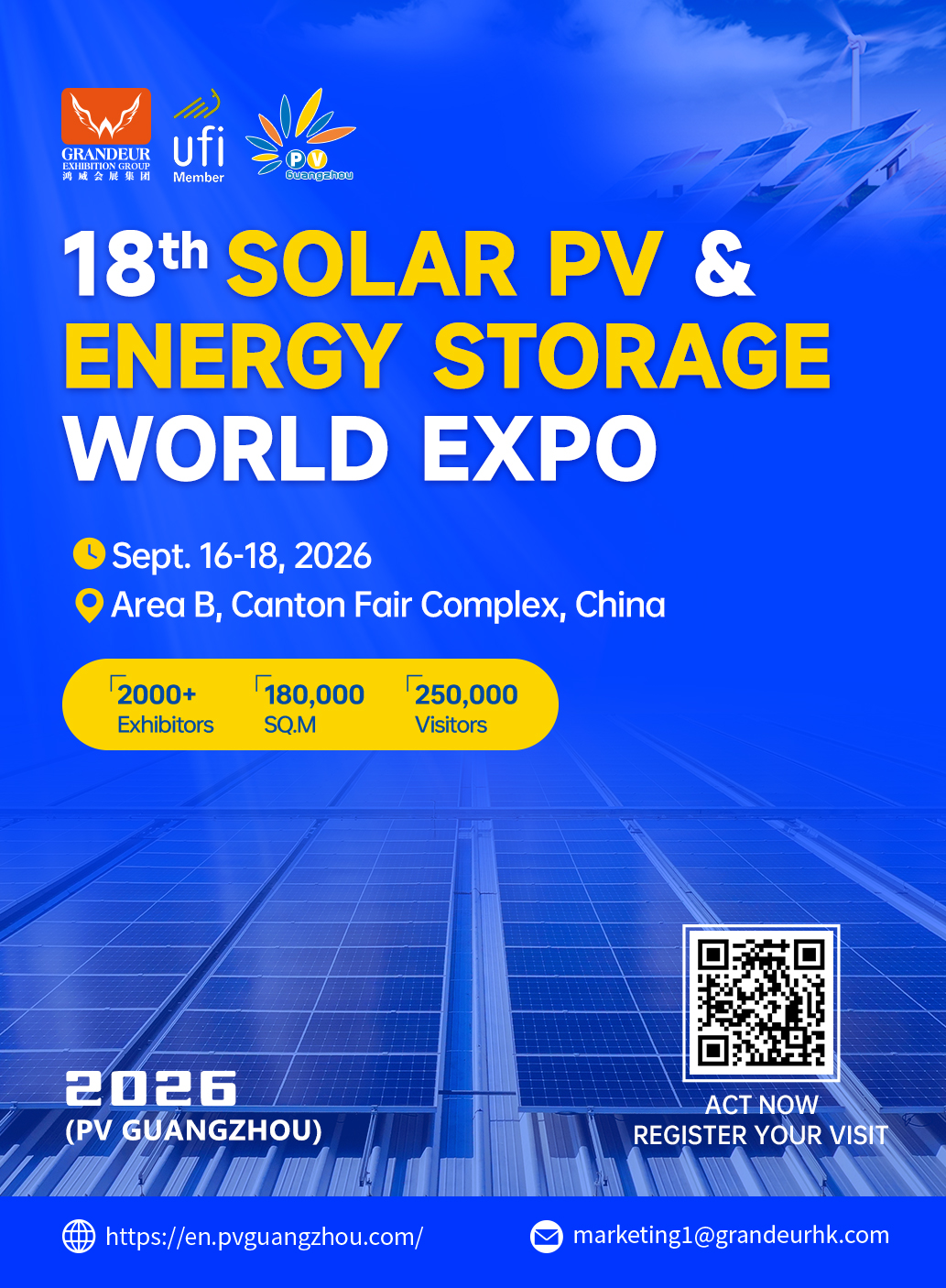Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah bekerja di Kementerian Kehutanan)
Ecobiz.asia – Indonesia beruntung memiliki etalase hutan yang lengkap, mulai dari pantai hingga hutan hujan dataran tinggi. Dua ekosistem unik yang selalu tergenang air meski dengan karakteristik berbeda adalah mangrove dan gambut. Keduanya dikenal sebagai ekosistem penyerap karbon terbesar dibandingkan hutan tropis lainnya.
Mangrove tumbuh di kawasan pantai, tetapi tidak semua pantai memilikinya. Hutan mangrove memiliki ciri khusus: tanah berlumpur akibat sedimentasi, tergenang air laut secara berkala, mendapat pasokan air tawar dari daratan, terlindung dari gelombang besar, serta memiliki kadar garam payau hingga asin.
Hutan sekunder mangrove mampu menyimpan 54,1–182,5 ton karbon per hektare, atau 3–5 kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis. Sebagai perbandingan, kebakaran gambut di Indonesia pada 1997–1998 melepaskan hingga 2,5 miliar ton karbon setara CO₂, sementara kebakaran 2002–2003 melepaskan 200 juta hingga 1 miliar ton.
Sayangnya, kedua ekosistem ini telah mengalami degradasi yang memprihatinkan. Dari 13,4 juta hektare lahan gambut di Indonesia, hanya 2,5 juta hektare yang masih alami. Sementara itu, data 2019 menunjukkan luas tutupan mangrove 3,56 juta hektare, terdiri atas 2,37 juta hektare dalam kondisi baik dan 1,19 juta hektare rusak.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 dengan mandat merestorasi 2 juta hektare gambut di tujuh provinsi. Pada 2020, mandat diperluas dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk merestorasi 1,2 juta hektare gambut serta merehabilitasi 600 ribu hektare mangrove di enam provinsi. Meski capaian restorasi gambut belum signifikan, BRGM berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pembentukan 110 Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan 220 Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM).
Khusus rehabilitasi mangrove, BRGM mencatat capaian 600 ribu hektare hingga 2023. Sementara itu, Kementerian Kehutanan pada 2020 melakukan penanaman mangrove seluas 15 ribu hektare. Karena BRGM bersifat ad hoc, pada era pemerintahan Prabowo–Gibran lembaga ini tidak dilanjutkan. Tugas rehabilitasi kini diambil alih oleh Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH).
Kondisi Ekosistem Mangrove Saat Ini
Kepala BRGM Hartono dalam acara Mangrove for Future (26/7/2024) menyebutkan bahwa mangrove di Indonesia terancam deforestasi. Citra satelit 1980–2010 menunjukkan kehilangan mangrove yang masif. Penelitian Badan Standardisasi Instrumen Kementerian Kehutanan memperkirakan pada 2021–2030 akan terjadi deforestasi tambahan sebesar 299.258 hektare, atau sekitar 29 ribu hektare per tahun.
Penyebab utamanya adalah belum adanya pengaturan tata ruang ekosistem mangrove secara komprehensif. Padahal, sesuai amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, kawasan mangrove seharusnya masuk kategori kawasan lindung. Artinya, hutan mangrove yang masih ada tidak boleh ditebang, baik secara legal maupun ilegal.
Meski pemerintah telah melakukan rehabilitasi ratusan ribu hektare, keberhasilan tumbuh belum terjamin selama deforestasi tetap berlangsung. Karena itu, regulasi dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci. Pemerintah akhirnya menerbitkan PP No. 27/2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang menjadi pedoman baru dalam tata kelola mangrove nasional.
Strategi Rehabilitasi Mangrove Nasional
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dalam media briefing (24/7/2025) memaparkan strategi rehabilitasi mangrove berbasis prinsip 3M: Memulihkan, Meningkatkan, dan Mengembangkan. Prinsip ini merujuk pada PP No. 26/2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi.
Target RHL Mangrove Indonesia berdasarkan RU-RHL adalah:
- 79,56% berada di kawasan hutan negara, menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan.
- 20,44% berada di luar kawasan hutan (APL), melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Namun, capaian rehabilitasi menghadapi tantangan serius: keterbatasan anggaran APBN, terbatasnya masa program hibah/loan, serta minimnya kapasitas pemeliharaan di lokasi terpencil. Untuk itu, strategi tidak hanya berfokus pada penanaman, melainkan diperluas menjadi investasi jangka panjang dengan melibatkan dunia usaha, lembaga donor, dan masyarakat.
Kebijakan ini dirumuskan dalam paket: Terobosan Pendanaan, Kolaborasi, dan Regulasi Adaptif, yang dituangkan dalam Peta Arahan Kebijakan Investasi dan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove. Pendekatan ini menempatkan rehabilitasi mangrove sebagai bagian integral dari pembangunan rendah emisi, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030.
Kemenhut juga menekankan pentingnya public engagement agar masyarakat ikut berperan aktif. Dukungan dari program multilateral dan CSR swasta dibuka lebar untuk memastikan rehabilitasi mangrove menjadi gerakan bersama, bukan sekadar proyek pemerintah.
Catatan untuk Rencana Strategis
Membaca rencana strategis rehabilitasi mangrove nasional dan menelaah PP No. 27/2025, ada sejumlah catatan penting yang harus dicermati agar strategi tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan belaka:
- Kesesuaian regulasi
Suka tidak suka, strategi rehabilitasi mangrove nasional harus tunduk pada koridor hukum yang sudah jelas: PP No. 27/2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove serta PP No. 26/2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Tanpa kepatuhan ini, kebijakan berisiko kontradiktif dengan payung hukum yang berlaku. - Definisi rehabilitasi
PP No. 27/2025 menyebut rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari pemulihan ekosistem, sejajar dengan restorasi, suksesi alami, perlindungan habitat, maupun cara lain berbasis sains dan teknologi. Sedangkan PP No. 26/2020 menegaskan bahwa rehabilitasi hutan adalah reboisasi dan konservasi tanah. Dalam konteks mangrove, rehabilitasi berarti reboisasi di kawasan yang sudah rusak—bukan sekadar aktivitas konservasi tanah. Penegasan definisi ini penting agar tidak terjadi bias dalam implementasi lapangan. - Metode reboisasi
Reboisasi mangrove tidak hanya berarti penanaman bibit di kawasan kosong, melainkan bisa dilakukan melalui dua pendekatan: reboisasi intensif di area kritis dan silvofishery, yaitu integrasi tambak dengan sistem empang-parit yang memungkinkan pemulihan ekosistem sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Tanpa pilihan metode yang adaptif, rehabilitasi akan rawan gagal. - Fokus kelembagaan
Direktorat Rehabilitasi Mangrove Kemenhut kini menjadi otoritas tunggal. Tugas utamanya bukan hanya melanjutkan capaian BRGM (600 ribu ha mangrove ditanam 2020–2025), tetapi juga mengevaluasi keberhasilan tumbuh, tingkat kelangsungan hidup, dan metodologi penanaman yang digunakan. Strategi baru harus mampu menjawab pertanyaan: berapa persen tanaman yang benar-benar tumbuh, bukan sekadar berapa hektare yang ditanam. - Tanggung jawab pemerintah
Rehabilitasi mangrove dalam kawasan hutan negara yang tidak dibebani hak perizinan adalah kewajiban penuh pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan masyarakat hanya relevan di luar kawasan hutan, sementara keterlibatan investor tidak bisa semata-mata untuk “menanam mangrove”. Skema investasi hanya masuk akal jika disertai model pengelolaan berkelanjutan, seperti silvofishery berbasis izin kelola terbatas. - Kejelasan target dan pemeliharaan
Strategi nasional harus menetapkan target yang terukur: luas penanaman baru, mekanisme pemeliharaan, serta evaluasi tanaman hasil rehabilitasi sebelumnya. Data menunjukkan KLHK menanam 150 ribu ha dan BRGM 600 ribu ha, tetapi seberapa besar yang berhasil tumbuh? Tanpa kepastian pemeliharaan, capaian luas tanam hanya menjadi angka di atas kertas. - Risiko strategi yang sekadar wacana
Jika catatan-catatan di atas tidak dijadikan pijakan, strategi rehabilitasi mangrove nasional hanya akan berakhir sebagai diskursus tanpa dampak nyata. Padahal, mangrove adalah benteng penting dalam menghadapi krisis iklim global sekaligus penyerap karbon raksasa. Ketidakjelasan arah hanya akan memperpanjang daftar kegagalan program rehabilitasi sebelumnya. ***