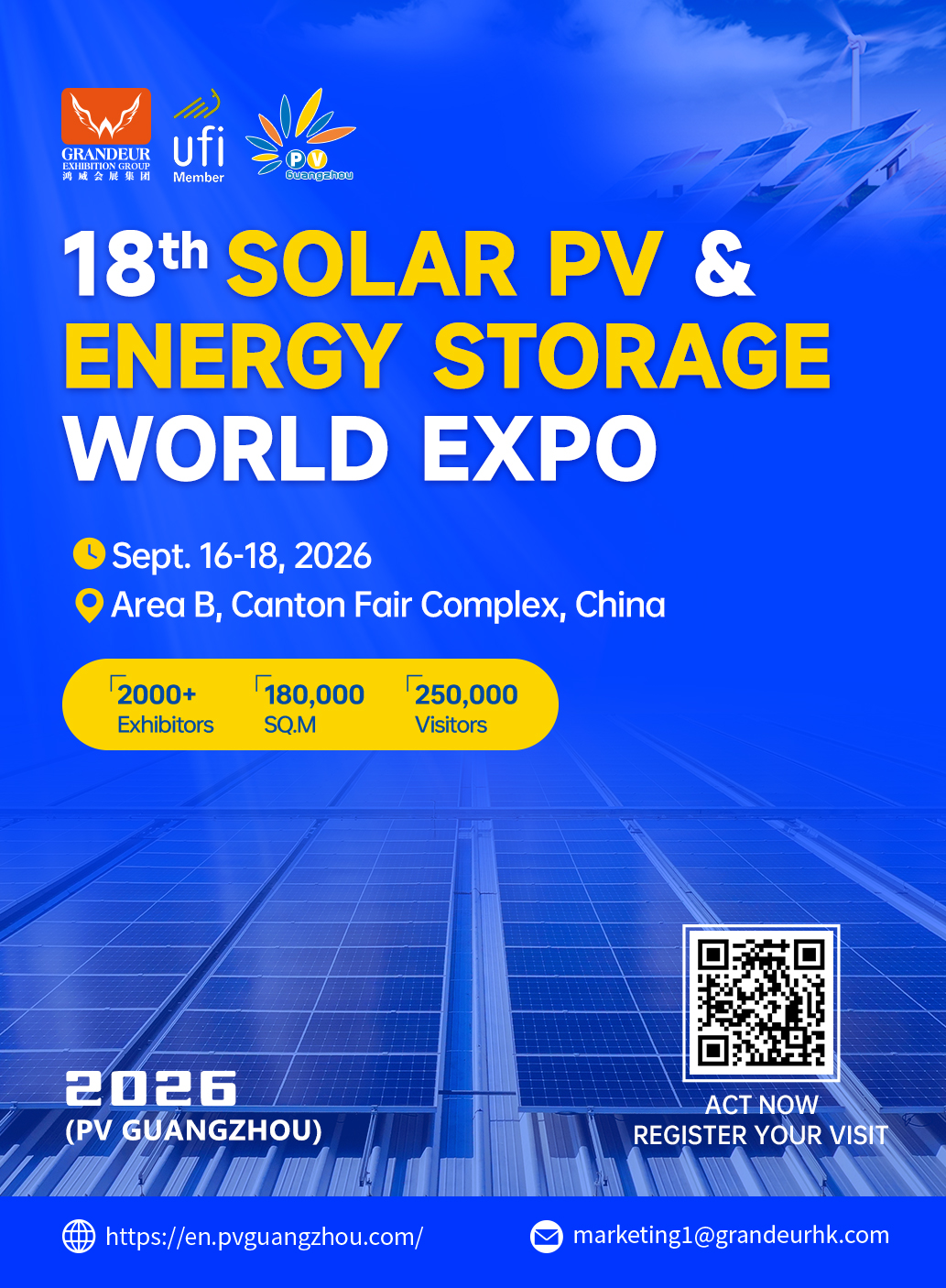Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
Ecobiz.asia – Reformasi regulasi kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat adat. Banyak komunitas yang tinggal turun-temurun di dalam dan sekitar hutan belum diakui secara sah oleh negara. Hal ini tampak dari penolakan masyarakat adat Dayak Meratus terhadap rencana pemerintah menetapkan Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, sebagai taman nasional. Dari 119.779 hektare yang diusulkan, lebih dari separuh merupakan wilayah adat mereka.
Meski UU No. 41/1999 tentang Kehutanan telah direvisi melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan UU No. 5/1990 direvisi menjadi UU No. 32/2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat (MHA) masih luput. Upaya judicial review oleh AMAN, WALHI, KIARA, dan tokoh adat pun ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).
Logika Terbalik Hutan Adat
Kasus Meratus mengingatkan pada Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) di Yogyakarta. Masyarakat Kaliurang telah lama bermukim di sana, jauh sebelum Merapi ditetapkan sebagai taman nasional pada 2004. Meski aturan menegaskan zona inti taman nasional harus steril dari pemukiman, faktanya hingga kini warga tetap tinggal dan pariwisata berjalan. Ini contoh kebijakan afirmatif.
Namun, kebijakan serupa tidak berlaku di banyak daerah lain. Kasus Efendi Buhing dari Desa Kinipan, Kalimantan Tengah, menunjukkan logika terbalik. Pemerintah daerah menyatakan tidak ada hutan adat di Kinipan karena belum ada permohonan resmi. Padahal, masyarakat adat sudah ada turun-temurun jauh sebelum hadirnya perusahaan sawit. MK melalui putusan No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan hutan adat bukan lagi hutan negara. Sayangnya, Pasal 67 UU No. 41/1999 masih mensyaratkan pengakuan melalui Perda, sehingga pelaksanaan keputusan MK tersendat.
Afirmasi dalam UU Cipta Kerja
UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja membawa sejumlah kebijakan afirmatif, antara lain perhutanan sosial yang diatur dalam Pasal 29A–29B. Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi oleh perseorangan, kelompok tani, maupun koperasi. Dalam Permen LHK No. P.83/2016, perhutanan sosial mencakup hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat.
Namun, regulasi terbaru justru mempersempit ruang. PP No. 23/2021 tidak lagi memasukkan hutan konservasi sebagai wilayah perhutanan sosial, padahal PP No. 6/2007 sebelumnya masih memungkinkan.
Yang Tertinggal
UU Cipta Kerja tidak menyentuh persoalan paling mendasar: Pasal 67 UU No. 41/1999. Padahal, putusan MK 2012 sudah mengubah status hutan adat. Sayangnya, pengukuhan MHA masih harus melalui Perda, yang dalam praktiknya sulit karena kepentingan ekonomi lebih dominan.
Masyarakat adat hanya disebut sekilas dalam Pasal 37 UU Cipta Kerja, yang mendefinisikan mereka sebagai paguyuban tradisional dengan pranata hukum adat dan hak memungut hasil hutan, tetapi tetap bergantung pada pengesahan Perda.
UU Cipta Kerja tidak menyentuh persoalan paling mendasar: Pasal 67 UU No. 41/1999. Padahal, putusan MK 2012 sudah mengubah status hutan adat.
Tumpuan Terakhir
Sebagai negara yang menargetkan Indonesia Emas 2045, sudah saatnya pemerintah serius menghormati Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang telah berlaku hampir dua dekade. RUU Masyarakat Adat yang mandek 14 tahun harus segera disahkan menjadi undang-undang.
Kementerian Dalam Negeri perlu memonitor implementasi pengakuan masyarakat adat di daerah, sementara Kementerian Kehutanan harus memperluas kerja sama dengan pemda untuk pengakuan hutan adat. Pemda juga perlu menyiapkan lembaga khusus berikut anggarannya.
Bagi masyarakat Dayak Meratus, tumpuan terakhir adalah RUU MHA yang ditargetkan sah pada 2025. Harus ada pasal yang menjamin mereka tetap hidup di wilayah adatnya meski Pegunungan Meratus ditetapkan sebagai taman nasional, dengan kewajiban menjaga ekosistem. Dengan begitu, konservasi dan kehidupan masyarakat adat dapat berjalan harmonis. ***