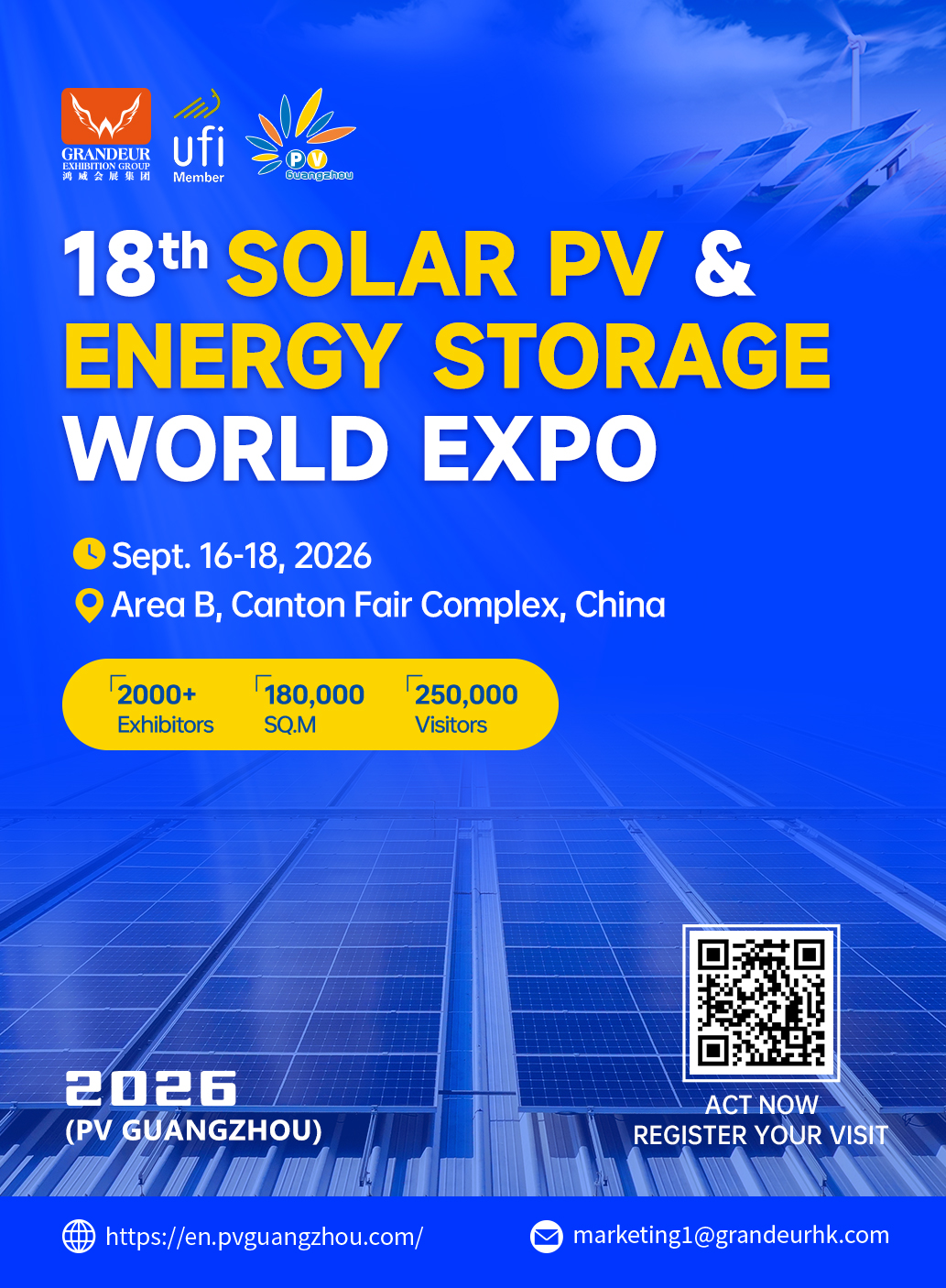Oleh: Diah Suradiredja (Pemerhati perdagangan komoditas berkelanjutan)
Ecobiz.asia – Regulasi EUDR sejak awal dipuji sebagai tonggak sejarah keberanian Uni Eropa dalam memimpin agenda global melawan deforestasi. Namun, hanya dua tahun sejak disahkan, realitas politik dan teknis mulai menguji ketahanan ambisi tersebut. Surat resmi Komisioner Jessika Roswall yang mengusulkan penundaan selama setahun menyingkap dilema mendasar: apakah Uni Eropa mampu menjaga kredibilitas ambisi hijaunya, ataukah ia akan menyerah pada tekanan internal dan eksternal?
Di satu sisi, Uni Eropa ingin menampilkan dirinya sebagai “climate leader” yang konsisten dengan Green Deal. EUDR didesain untuk menekan deforestasi global, dengan mekanisme due diligence ketat, traceability berbasis poligon, hingga kewajiban pengawasan rantai pasok bagi importir. Semua itu ditujukan untuk memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar Eropa benar-benar bebas dari jejak deforestasi.
Namun di sisi lain, tekanan politik domestik semakin keras. Para petani Eropa melakukan protes terbuka, terutama di Perancis, Italia, dan Polandia, karena merasa regulasi hijau justru menambah biaya dan memperburuk krisis harga pangan. Negara-negara Eropa Timur seperti Hungaria, Polandia, dan Slovakia bersuara lantang menolak implementasi penuh, dengan alasan EUDR lebih menguntungkan negara-negara kaya di Eropa Barat. Sebaliknya, Jerman, Belanda, dan negara-negara Nordik cenderung lebih mendukung penerapan EUDR secara ketat. Perpecahan Barat–Timur ini memperlihatkan bahwa EUDR bukan hanya soal lingkungan global, melainkan juga medan perebutan kepentingan ekonomi-politik internal Uni Eropa.
Tekanan juga datang dari industri besar, mulai dari pengolahan agribisnis, sektor ritel, hingga perbankan, yang menilai biaya kepatuhan bisa mencapai miliaran euro per tahun. UMKM Eropa khawatir tersingkir karena tidak mampu mengikuti sistem digital dan persyaratan pelacakan yang kompleks.
Ketidakselarasan ini menjadikan EUDR sebagai arena tarik-menarik kepentingan. Di sisi lain, LSM lingkungan menuntut agar ambisi awal dipertahankan tanpa kompromi, karena melonggarkan EUDR berarti mengorbankan kredibilitas Eropa dalam agenda iklim global. Sebaliknya, politisi dan industri mendorong penyederhanaan melalui Omnibus Package, agar beban administrasi bisa dikurangi dan dampaknya terhadap daya saing ekonomi Eropa dapat diminimalisasi.
Kondisi ini membuat EUDR berada di persimpangan berbahaya:
- Jika tetap dipaksakan tanpa penyesuaian, sistem IT yang kolaps bisa menimbulkan krisis kepatuhan massal, merusak kepercayaan pasar, dan menghambat perdagangan internasional.
- Jika terlalu banyak kompromi, EUDR berisiko berubah dari instrumen ambisius menjadi sekadar simbol politik yang kehilangan taringnya.
Namun tarik-menarik ini tidak berhenti di ruang debat politik. Komisi Eropa lalu memainkan kartu baru: Omnibus Package. Diluncurkan sebagai “jalan pintas” untuk menenangkan industri dan meredakan keresahan negara anggota, omnibus dipasarkan sebagai solusi kompromi antara ambisi hijau dan realitas ekonomi. Tapi benarkah ia jembatan penyeimbang, atau justru sebuah kuda Troya yang perlahan menggerogoti kredibilitas EUDR dari dalam? Seperti diingatkan European Environmental Bureau (EEB), “simplification is just a Trojan horse for aggressive deregulation.” Pertanyaan inilah yang membawa kita pada perdebatan berikutnya: Omnibus, jalan tengah atau jalan buntu?
Omnibus: Jalan Tengah atau Jalan Buntu?
Pada 26 Februari 2025, Komisi Eropa resmi meluncurkan Omnibus Package sebagai upaya “revolusi penyederhanaan” regulasi, dengan janji memangkas beban administrasi hingga 25% untuk seluruh perusahaan dan 35% khusus untuk UMKM. Di atas kertas, gagasan ini tampak sebagai win-win solution: regulasi tetap berjalan, tetapi lebih ringan bagi dunia usaha. Namun, apakah benar omnibus akan menjadi jalan tengah yang efektif, atau justru jalan buntu yang mengorbankan ambisi iklim?
Dukungan politik terhadap omnibus datang dari berbagai arah. 18 kementerian pertanian negara anggota UE menuntut agar EUDR masuk ke dalam paket ini, dengan alasan persyaratan uji tuntas terlalu rumit dan tidak realistis. Industri besar Eropa melalui Business Europe, Copa Cogeca, dan Fediol juga mendorong penyederhanaan karena khawatir biaya kepatuhan mencapai miliaran euro per tahun dan memperlemah daya saing Eropa di pasar global.
Namun, dari sisi lain, LSM lingkungan justru menentang keras. Beberapa pernyataan nyata:
Earthsight mengingatkan bahwa “standar lingkungan tidak boleh di-roll back atas nama ‘penyederhanaan’” dan bahwa memasukkan EUDR ke omnibus “merupakan risiko melemahkan undang-undang penting yang dirancang untuk melindungi hutan, biodiversitas, dan iklim.”
Koalisi NGO termasuk ClientEarth, Friends of the Earth Europe, ECCJ, Anti-Slavery International, Clean Clothes Campaign, Global Witness, Notre Affaire À Tous, dan T&E menyatakan, “The Omnibus proposal was made without any public consultation, sidelining civil society, with a lack of evidence or environmental and social impact assessments, and with a primary focus on narrow industry interests.”
Dalam kritik yang lebih tajam, European Environmental Bureau (EEB) menyebut, “It is now clear that ‘simplification’ is just a Trojan horse for aggressive deregulation … gratification for corporate interests … legal uncertainty, rewarding laggards while penalising companies that were moving early to monitor and report their environmental impact.”
Selain itu, Virginie Rouas (Policy Officer ECCJ) menyatakan, “This so-called ‘Simplification Omnibus’ is anything but simple, it risks making companies’ lives more complicated and rewards laggards over those already making efforts to transition.”
Dengan benturan kepentingan ini, muncul paradoks: Omnibus bisa menjadi jalan tengah jika benar-benar menghasilkan regulasi yang tetap menjaga ambisi iklim namun lebih mudah diterapkan. Tetapi omnibus juga berpotensi menjadi jalan buntu, jika penyederhanaan berubah menjadi kompromi politik yang menguntungkan industri tetapi merusak kredibilitas Eropa sebagai pemimpin iklim global.
Bagi Indonesia, pertaruhan omnibus ini juga penting. Jika penyederhanaan benar-benar efektif, eksportir bisa mendapat ruang bernafas lebih longgar dalam memenuhi kewajiban traceability. Tetapi jika omnibus gagal menjawab ketegangan politik atau menjadi mesin kompromi, risiko terbesar adalah EUDR berubah menjadi regulasi yang kabur, berubah-ubah, penuh ketidakpastian, dan makin sulit diprediksi arah implementasinya — sebuah kondisi yang sama bahayanya dengan regulasi yang terlalu ketat.
Di tengah ketidakpastian apakah omnibus akan menjadi solusi atau justru jebakan deregulasi, perhatian juga tertuju pada bagaimana negara anggota UE sendiri mempersiapkan diri. Sebab, seketat apa pun aturan dari Brussels, implementasi sejati selalu terjadi di lapangan, di tangan otoritas kompeten tiap negara. Dari sinilah terlihat warna yang beragam: ada yang memilih jalur edukatif dan bertahap, ada pula yang mengambil pendekatan progresif bahkan keras sejak awal. Kontras antara Finlandia dan Belanda menjadi cermin penting untuk membaca arah penerapan EUDR, sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi negara produsen seperti Indonesia.
Kesiapan Negara Anggota: Belajar dari Finlandia dan Belanda
Pelaksanaan EUDR di tingkat negara anggota menunjukkan variasi pendekatan yang mencolok. Finlandia dan Belanda adalah dua contoh ekstrem yang memberikan gambaran bagaimana regulasi tunggal bisa diimplementasikan dengan cara yang berbeda sesuai konteks domestik masing-masing.
Finlandia mengambil pendekatan yang hati-hati dan bertahap. Melalui Finnish Food Agency, pemerintah Finlandia menyelenggarakan berbagai diskusi multipihak dengan fokus pada sektor berisiko tinggi seperti sapi dan kayu. Bea Cukai Finlandia bahkan sudah menyiapkan sesi informasi mengenai tata cara deklarasi produk EUDR, lengkap dengan terjemahan FAQ ke bahasa lokal. Strategi ini menunjukkan bahwa Finlandia lebih menekankan pada edukasi dan penguatan kapasitas pelaku usaha agar mereka paham kewajiban baru. Dengan kata lain, Finlandia membangun kepatuhan melalui pembelajaran, bukan sekadar pengawasan.
Sebaliknya, Belanda menempuh jalur yang lebih progresif, bahkan agresif. Otoritas Kompetennya, Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA), membuka ruang bagi sistem pemantauan independen swasta sebagai pelengkap mekanisme kontrol resmi. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi operator dan pedagang, tetapi dengan catatan penting, yaitu sertifikasi swasta tidak otomatis berarti kepatuhan hukum. NVWA juga melakukan pilot audit terhadap 25 perusahaan di enam komoditas, dan hasilnya mengejutkan: hanya 40% perusahaan yang memenuhi syarat EUDR. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan tidak bisa sekadar “dibeli” melalui sertifikasi atau platform digital; uji tuntas harus benar-benar terintegrasi dalam operasi bisnis sehari-hari.
Catatan pembelajaran dari kesiapan dua negara ini adalah: model Finlandia relevan untuk konteks pembinaan petani kecil — edukasi, pelatihan, dan bantuan teknis menjadi kunci agar mereka tidak terlempar dari rantai pasok global. Indonesia dapat meniru strategi ini dengan memperkuat helpdesk nasional, menerjemahkan panduan teknis EUDR, serta menyiapkan dashboard komoditas strategis sebagai alat bantu adaptasi.
Model Belanda menjadi peringatan bahwa pasar utama seperti Belanda akan menerapkan standar yang jauh lebih ketat. Artinya, sertifikasi (ISPO, RSPO, ISCC) harus diintegrasikan dengan sistem traceability nasional, bukan berdiri sendiri. Indonesia juga harus mendorong agar ISPO diakui formal dalam kerangka verifikasi risiko EUDR, sehingga tidak kalah legitimasi dibandingkan standar internasional.
Namun yang paling penting, Indonesia harus siap menghadapi ketidakseragaman implementasi di negara anggota UE. Ada yang lunak seperti Finlandia, ada pula yang keras seperti Belanda. Diplomasi bilateral dengan negara kunci (Belanda, Jerman, Italia) menjadi sama pentingnya dengan diplomasi di tingkat Brussel.
Dengan memahami kontras antara Finlandia dan Belanda, Indonesia dapat menyusun strategi yang lebih adaptif: menggabungkan edukasi dan pembinaan di tingkat petani, sambil memperkuat diplomasi dan pengakuan sistem nasional. Pendekatan ganda ini akan menjadi fondasi agar produk strategis Indonesia tetap memiliki akses pasar yang kuat di Eropa, meski regulasi semakin ketat.
Dampaknya untuk Indonesia: Risiko atau Peluang?
Bagi Indonesia, EUDR menghadirkan wajah ganda: ancaman yang bisa menutup pintu ekspor sekaligus peluang untuk memperkuat posisi dalam tata kelola keberlanjutan global. Namun risiko terbesar ada pada level teknis dan kelembagaan. Persyaratan traceability hingga ke titik asal lahan berbasis poligon masih menjadi batu sandungan. Regulasi nasional terkait data spasial belum sepenuhnya memungkinkan keterbukaan, sementara jutaan petani kecil tidak memiliki dokumen formal kepemilikan atau akses teknologi digital. Jika standar EUDR dipaksakan tanpa adaptasi, maka petani kecil terancam tersingkir dari rantai pasok karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang mahal dan rumit. Ini berarti Indonesia bisa kehilangan sebagian pangsa pasar strategis di Uni Eropa, terutama pada komoditas sawit, kakao, kopi, dan karet.
Namun di balik tantangan ini terdapat peluang strategis. Penundaan EUDR dan wacana Omnibus memberi waktu tambahan untuk memperkuat instrumen domestik:
National Dashboard Komoditas Strategis dapat menjadi mekanisme verifikasi risiko yang mengurangi ketergantungan pada data poligon terbuka. Dengan pendekatan ini, status kepatuhan bisa ditampilkan dalam kategori “compliant” atau “non-compliant” tanpa melanggar kedaulatan data nasional.
ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) bisa didorong agar diakui sebagai standar uji tuntas yang sahih. Jika berhasil, ISPO akan menjadi penyeimbang RSPO dan sertifikasi internasional lain yang lebih dominan di pasar Eropa.
Diplomasi koalisi produsen (Indonesia, Malaysia, Brasil, Kolombia) semakin relevan. Dengan memanfaatkan retaknya konsensus politik internal UE, Indonesia bisa mendorong model keberlanjutan yang lebih inklusif dan realistis.
Dengan kata lain, EUDR adalah stress test bagi Indonesia: apakah negara akan terjebak dalam narasi sebagai “korban regulasi”, atau justru tampil sebagai arsitek solusi yang menunjukkan bahwa keberlanjutan bisa dicapai tanpa mengorbankan jutaan petani kecil. Jika dikelola dengan cerdas, EUDR dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kredibilitas tata kelola komoditas berkelanjutan sekaligus menegaskan posisinya sebagai mitra sejajar, bukan sekadar pemasok yang tunduk pada aturan eksternal.
Di tengah tarik-menarik antara LSM dan industri Eropa, Indonesia dapat menawarkan jalan tengah, yaitu regulasi hijau yang ambisius tetapi realistis dan inklusif bagi petani kecil. Narasi ini bisa mengubah posisi Indonesia dari sekadar pihak yang “tertekan regulasi” menjadi mitra solusi bagi Uni Eropa.
Di tengah tarik-menarik antara LSM dan industri Eropa, Indonesia dapat menawarkan jalan tengah, yaitu regulasi hijau yang ambisius tetapi realistis dan inklusif bagi petani kecil.
Kuncinya adalah mengambil peran aktif, memperkuat instrumen domestik seperti ISPO dan National Dashboard, menjalin aliansi dengan negara produsen lain, serta menggunakan diplomasi cerdas untuk memengaruhi perdebatan internal di Uni Eropa. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya menjaga akses pasar, tetapi juga menegaskan dirinya sebagai aktor penting dalam tata kelola hijau global.
Singkatnya, EUDR bukan akhir permainan, melainkan awal babak baru. Babak di mana Indonesia bisa membuktikan bahwa keberlanjutan tidak harus eksklusif, mahal, atau menyingkirkan petani kecil, tetapi bisa inklusif, adil, dan tetap ambisius. Jika Uni Eropa sedang diuji konsistensinya, maka Indonesia sedang diuji kecerdikan diplomasi dan kapasitas domestiknya. Dan siapa yang berhasil melewati ujian ini, dialah yang akan diakui dunia sebagai pemimpin sejati dalam transisi hijau global. ***